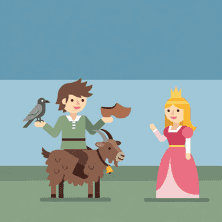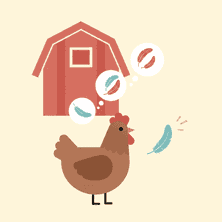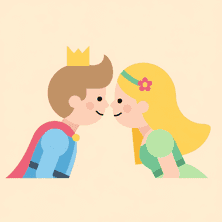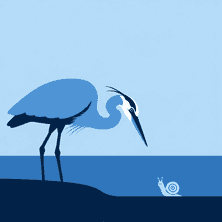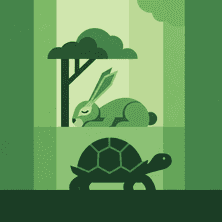Gadis yang Menginjak Roti
Pernah ada seorang gadis miskin bernama Inger. Dia memiliki mata yang cerah dan wajah yang cantik, dan orang-orang sering berkata dia adalah anak terindah di desa. Tetapi Inger bangga. Dia menyukai cara pita halus dan sepatu rapi membuatnya merasa lebih penting daripada orang lain. Dia tidak berterima kasih kepada mereka yang membantunya, dan dia memandang rendah siapa pun dengan pakaian bertambal atau sepatu bot berlumpur.
Seorang wanita baik di kota menerima Inger ke rumahnya sebagai pelayan. Inger diberi makan dengan baik di sana dan mengenakan gaun bersih. Semakin nyaman hidupnya, semakin bangga dia tumbuh. Dia melupakan pondok tempat orang tuanya tinggal. Dia lupa bagaimana rasanya lapar, atau menginginkan selendang hangat. Dia lupa untuk menjadi baik.
Suatu hari majikannya berkata, "Inger, kunjungi orang tuamu dan bawakan mereka roti besar ini." Inger mengenakan sepatu terbaiknya dan pita yang paling dia sukai. Dia memegang roti itu dengan hati-hati, bukan karena itu berharga, tetapi karena dia tidak ingin tepung di gaunnya. Langit berwarna abu-abu, dan jalan setapak melintasi ladang lunak dan basah karena hujan. Di antara jalan dan pondok-pondok terbentang tempat rawa yang luas dengan batu loncatan di seberangnya. Air berputar di sekitar batu hari itu.
Ketika Inger mencapai tepi rawa, dia berhenti. Batu loncatan itu licin, dan lumpurnya dalam. Dia melihat sepatunya—begitu baru, begitu mengkilap—dan dia hanya berpikir untuk menjaganya tetap bersih. Inger melirik roti di tangannya. "Roti itu besar dan keras," katanya pada dirinya sendiri. "Itu akan menjadi batu loncatan yang bagus. Saya bisa menyekanya sesudahnya. Tidak ada yang akan tahu." Dalam hatinya dia tahu itu salah. Roti adalah hadiah yang dimaksudkan untuk memberi makan mulut yang lapar. Tetapi kesombongan adalah hal yang berat.
Dia meletakkan roti itu di atas air berlumpur dan meletakkan kakinya di atasnya. Roti itu tenggelam sedikit. Dia melangkah dengan kaki lainnya—dan tenggelam lebih dalam. Air menarik pergelangan kakinya dan kemudian lututnya. Dia berteriak, tetapi tidak ada orang di dekatnya yang mendengar. Roti itu tenggelam, dan bersamanya pergi Inger—turun di luar alang-alang dan air hitam, turun di mana matahari tidak bisa menjangkau.
Di bawah rawa adalah tempat yang dingin dan redup. Katak bernyanyi dan serangga berdengung. Di aula bayangan, Wanita Rawa duduk di ramuannya yang menggelegak. Dialah yang menangkap hal-hal yang dibuang orang—hal-hal baik yang diperlakukan dengan buruk—dan dia menyimpannya sebagai pelajaran. "Ah," kata Wanita Rawa, mengintip Inger. "Seorang gadis yang menginjak roti agar dia tidak mengotori sepatunya. Hatimu lebih keras dari tanah liat." Dia meletakkan Inger di atas batu seperti patung. Inger tidak bisa menggerakkan jari. Dia tidak bisa menghapus matanya, meskipun perih. Dia hanya bisa mendengar dan berpikir.
Waktu berlalu, meskipun Inger tidak tahu seberapa banyak. Di dunia di atas, orang-orang menceritakan kisah itu. "Jangan menjadi seperti gadis yang menginjak roti," beberapa memarahi. Yang lain tertawa dan membuat lelucon. Tetapi beberapa anak menekan tangan mereka bersama-sama dan berbisik, "Inger yang malang." Kata-kata lembut mereka menyebar seperti tetesan hangat melalui bumi dan air. Mereka jatuh di dekat tempat Inger duduk, dan dia merasakannya seperti percikan kecil melawan dingin.
Burung kadang-kadang terbang rendah di atas rawa, dan sayap cepat mereka membawa berita. Burung layang-layang, beristirahat sejenak, berbicara lembut tentang sebuah pondok kecil dan dua orang tua. "Mereka masih menyebut namamu," kata burung layang-layang padanya. "Mereka malu, tetapi mereka sedih juga." Setiap kata menyakitkan, dan untuk pertama kalinya, rasa sakit itu bukan kebanggaan tetapi kesedihan. Jika saja dia bisa mengambil kembali satu langkah—jika saja dia bisa memberikan roti yang dimaksudkan untuk diberikan.
Katak dan serangga berdengung di sekelilingnya. Beberapa mengejeknya. "Roti adalah untuk dimakan," seru mereka. "Kamu membuatnya menjadi batu." Itu benar. Inger tidak punya jawaban. Dia mencoba menangis, tetapi air mata tidak mau keluar. Hatinya terasa seperti kerak yang keras dan kering. Kemudian suara seorang anak, jauh, mengucapkan doa untuknya—hanya beberapa kata sederhana. Tetesan hangat menyentuh pipi Inger. Akhirnya air mata nyata mengikutinya. Wanita Rawa mencoba menangkap air mata itu untuk ramuannya, tetapi itu jatuh dan menghilang ke bumi yang gelap seperti mutiara.
Satu air mata itu melunakkan sesuatu di dalam Inger. Dia berpikir, "Jika saya bisa melakukan satu hal baik—hanya satu." Wanita Rawa menyipitkan mata padanya. "Kamu sedang belajar," katanya, hampir terkejut. "Kamu akan menjadi seringan pikiran yang baru saja kamu miliki." Dan dalam sekejap, patung itu hilang. Inger adalah burung kecil berwarna cokelat keabu-abuan, polos seperti ranting. Suaranya tidak bisa menyanyikan lagu mewah. Itu hanya bisa membuat suara tipis dan bersemangat—"Tweet, tweet." Tetapi dia memiliki sayap.
Inger bangkit melalui gulma dan alang-alang dan akhirnya sampai ke udara terbuka. Sinar matahari menghangatkan bulunya. Dunia tampak baru dan luas, tetapi hati barunya terasa mantap dan kecil. Dia tidak terbang untuk menyombongkan kebebasannya. Dia terbang ke ambang jendela dan tangga pondok. Dia mengambil remah-remah yang ditinggalkan orang. Dia membawanya ke anak burung yang lapar. Dia menjatuhkannya ke tangan anak-anak miskin yang duduk di luar pintu. Dia menemukan pondok orang tuanya dan meninggalkan remah-remah di ambang pintu. Dia akan mengembalikan, remah demi remah, roti yang telah dia sia-siakan.
Orang-orang memperhatikan burung kecil yang sibuk itu. "Ia tidak pernah makan sebelum memberi," kata mereka. "Burung yang aneh." Beberapa menyebutnya burung roti, karena sepertinya selalu mengantarkan potongan roti kecil. Dia tidak bernyanyi seperti burung larks atau burung bulbul. Tetapi ketika dia membuat panggilannya yang tipis, itu terdengar seperti pesan: "Ingatlah yang lapar. Jadilah baik."
Banyak musim berlalu. Salju turun dan mencair; bunga mekar dan pudar; anak-anak tumbuh lebih tinggi. Burung kecil itu terus bekerja. Setiap remah yang diberikan terasa seperti bulu cahaya yang ditambahkan ke sayapnya. Setiap pemikiran baik dari seorang anak yang mendengar cerita lama dan berkata, "Inger yang malang," terasa seperti angin hangat.
Akhirnya, suatu pagi yang cerah, ketika dia telah membawa begitu banyak remah sehingga, bersama-sama, mereka akan seberat roti utuh, angin sepoi-sepoi mengangkat burung kecil itu lebih tinggi dari sebelumnya. Dia naik, melewati puncak pohon tertinggi, ke cahaya keemasan yang lembut. Sebuah suara seperti musim semi sepertinya berkata, "Kamu telah belajar kerendahan hati. Kamu telah belajar memberi."
Maka gadis yang pernah menginjak roti untuk menyelamatkan sepatunya dimaafkan dan diangkat ke sukacita. Orang masih menceritakan kisahnya—bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa kesombongan dapat menenggelamkan kita dengan cepat, dan bahwa kebaikan dan rasa syukur dapat membawa kita kembali ke cahaya.